Magister di Fakultas Humaniora? Sebuah Usulan
Menandaskan judulnya, artikel singkat ini memaparkan sekadar sebuah usulan, yakni dalam rangka Pembukaan Program Studi S2/Magister di Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara.
Usulan ini telah saya sampaikan secara tertulis kepada Fakultas Humaniora dan peserta rapat terkait pada 16 Oktober 2019 melalui surat elektronik, oleh karena saya berhalangan untuk memenuhi undangan rapat dalam rangka diskusi hal tersebut (18 Oktober 2019, pukul 10-12 WIB). Pada waktu yang bersamaan, saya mesti memberikan kuliah di Kampus BINUS Anggrek.
Demikian adalah ungkapan tertulis saya:
Saya telah membaca persyaratan pembukaan & nomenklatur Prodi Magister (saya lampirkan juga; barangkali ada gunanya bagi yang belum sempat mencarinya).
Beberapa hasil pembacaan saya adalah sbb:
Perlu perhatian pada Nomenklatur Sosial-Humaniora. Ada beberapa alternatif Program Studi, seperti:
- Studi Humanitas (Humanistic Studies/Liberal Arts)
- Kajian Sastra dan Budaya (Literature and Cultural Studies)
- Kajian Budaya (Cultural Studies)
- Kajian ASEAN (ASEAN Studies)
- Kajian Budaya dan Media (Cultural and Media Studies)
- Kajian Asia (Asian Studies)
- Kajian Indonesia (Indonesian Studies)
- Kajian Perkotaan (Urban Studies)
Melihat kekuatan Humaniora, saya berpendapat bahwa Kajian Perkotaan (Urban Studies) merupakan program studi yang membumi, realistik, dan dapat menunjukkan kontribusi nyata interdisiplin program-program studi dalam Fakultas Humaniora BINUS.
Gambaran Kurikulum Kajian Perkotaan dapat ditemukan di Universitas Indonesia:
- https://sksg.ui.ac.id/kajian-pengembangan-perkotaan (cuplikannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini)
- http://www.profilprodi.com/detail/001002-95125.html
Hanya saja, Universitas Indonesia lebih menguatkan kurikulumnya pada Aspek Sosial Sciences, sedangkan FHUM Binus dapat menguatkan pada Aspek Humanities (hal ini yang dapat membedakan Kajian Perkotaan BINUS dari Kajian Perkotaan UI)
Tulisan Pater J. Drost SJ (alm.) di Kompas tahun 2002 (saya membacanya sewaktu saya menjalani kuliah Ilmu Budaya Dasar di S1 Fakultas Psikologi UPI YAI), kiranya layak menjadi perhatian kita sebagai semangat awal untuk mendirikan S2 Humaniora. Beruntung, ada yang mendokumentasikannya secara daring. Saya salinkan di bawah ini.
Demikianlah beberapa komentar awal saya.
Penulis: Dr. Juneman Abraham
Catatan 27 November 2020:
Sifat Studi Perkotaan yang mengapresiasi keragaman warga kota sesuai dengan Visi Fakultas Humaniora sendiri, yakni Becoming a world class faculty in multicultural communication, law and international relationship based on ICT in continuos pursuit in innovation and enterprise by 2020.
Beberapa kegiatan Psikologi BINUS dalam rangka memajukan Psikologi Perkotaan dan mengusulkan Studi Perkotaan, antara lain:
- Menyelenggarakan kuliah tamu Pengantar Psikologi Perkotaan, bertajuk Intergroup Emotions and Behavioral Motives: The Strange Case of Anger and Fear, dengan mengundang Professor Dr. Roger Giner-Sorolla dari School of Psychology, University of Kent, Keynes College, Canterbury, United Kingdom (2015).
- Menyelenggarakan kuliah tamu Psikologi Perkotaan, bertajuk Storytelling, Cultural Heritage and Public Engagement (2016).
- Memaparkan makalah hasil penelitian dalam Forum Ilmiah Internasional Perkotaan (2014), bertajuk The Role of Psychology of Curiosity in Making up Digital Content Promoting Cultural Heritage among Youths.
- Berbicara dalam Seminar Nasional “Kesehatan Mental di Perkotaan” (2018).
- Mendiskusikan keterkaitan psikoteknologi dengan daya saing manusia urban Indonesia dalam cikal bakal pembentukan Pusat Kajian Psikoteknologi (2016).
Simak juga:
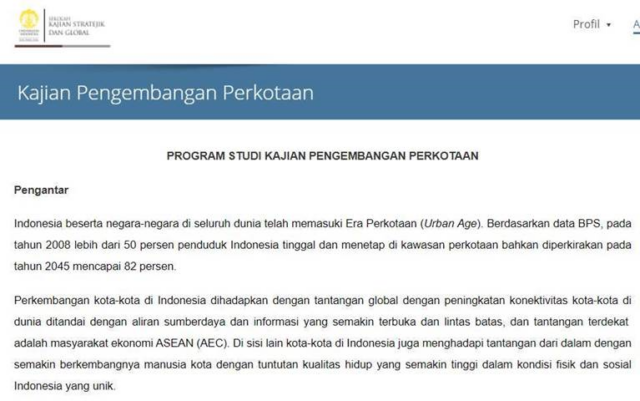
Urbanology, the study of urban problems.
Humaniora
Oleh: J Drost
APAKAH dalam pendidikan kita ada unsur humaniora? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu lebih dulu menjawab pertanyaan: “Apa itu humaniora?” Yang disebut human sciences, atau humanities, bukanlah humaniora. Bahkan, disiplin-disiplin yang tergolong dalam human sciences belum ada, ketika humaniora dibentuk.
Dalam humaniora klasik, bahasa tidak disebut sebagai disiplin. Maka, bahasa Latin bukan unsur humaniora. Bahasa Latin, yang karena perkembangan historis, merupakan bahasa yang dipakai sebagai lingua franca, seperti halnya bahasa Melayu yang dulu merupakan lingua franca di Indonesia. Bahkan bahasa Latin bukan merupakan bahasa “dasar”. Bahasa yang paling tua di Eropa dan sebagian dari Asia adalah bahasa Indo-European.
Bahasa Yunani, Celtic, Italic, Germanic, Slavic, Baltic, dan Indo-Iranian merupakan anak bahasa. Bahasa Latin adalah dialek dari bahasa Italic. Selain itu, bahasa Latin tidak pernah menghasilkan karya filosofis, drama, dan literatur yang berarti. Kebanyakan karya Latin adalah mengenai hukum, administrasi, dan politik.
Namun, karena suku Latinum berhasil merebut kekuasaan di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, mereka berhasil menjadikan bahasa Latin sebagai bahasa pemerintah dengan mendesak bahasa Yunani sebagai bahasa budaya. Karya Yunani tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan lewat Spanyol dari bahasa Arab ke bahasa Latin.
***
HUMANIORA, yang menjadikan manusia (humanus) lebih manusiawi (humanior), mula-mula terdiri atas gramatika, logika, dan retorika; trivium. Pada awalnya, segala tekanan diletakkan pada gramatika yang sering dipelajari selama tiga tahun lebih.
Ini terjadi karena penguasaan bahasa Latin (bahasa studi dan pergaulan di universitas, bukan bahasa ibu para mahasiswa) sama sekali belum cukup untuk mengomunikasikan hasil proses belajar. Dan, bila bahasa komunikasi tidak dikuasai secara mutlak, logika dan retorika tidak mungkin berjalan baik. Lama-kelamaan keadaan itu diubah; logika dan retorika ditekankan juga. Ada perkembangan dari trivium ke quadrivium: teologi, aritmetika, musik (teori akustik), dan astrologi (sekarang disebut astronomi).
Jadi, pendidikan humaniora bukan bahasa sebagai bahasa. Gramatika (tata bahasa) bermaksud membentuk manusia terdidik yang menguasai sarana komunikasi secara mutlak. Logika bermaksud membentuk manusia terdidik yang dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan sedemikian rupa hingga dapat diterima karena dapat dimengerti dan masuk akal. Retorika bermaksud membentuk manusia terdidik mampu merasakan perasaan dan kebutuhan pendengar, dan mampu menyesuaikan diri dan uraian dengan perasaan dan kebutuhan itu.
***
APA yang diharapkan dari humaniora zaman sekarang ini?
Sebagai bahan perbandingan, kiranya tidak salah bila kita dengar apa yang diharapkan dari calon mahasiswa oleh universitas-universitas di Jerman. Tuntutan itu dapat dipadatkan dalam satu kata hochschulreife. Semua calon harus telah mencapai hochschulreife, artinya: kematangan, baik intelektual maupun emosional, agar dapat menempuh studi akademis. Teras kematangan itu adalah kemampuan bernalar dan bertutur yang telah terbentuk.
Jadi, yang siap mulai studi di perguruan tinggi adalah dia yang dapat mengendalikan nalar, yaitu dia yang kritis. Seorang yang kritis adalah seorang yang, antara lain, mampu membedakan macam-macam pengertian dan konsep, sanggup menilai kesimpulan-kesimpulan tanpa terbawa perasaan, menolak perampatan-perampatan (generalisasi), tidak membeo semboyan-semboyan, dan tidak menerima propaganda sebagai pembuktian. Unsur lain yang perlu adalah kritik diri yang memungkinkan orang bernalar dan bertindak obyektif.
Ciri khas dari seseorang yang “matang” masuk perguruan tinggi di Indonesia adalah penguasaan bahasa Indonesia, baik saat bertutur maupun menulis. Tata bahasa dan ejaan harus dikuasai secara mutlak. Logika mencirikan segala cara berkomunikasi.
Bernalar dan bertutur diperoleh dan dibentuk terutama lewat matematika dan bahasa. Matematika mengajar kita bernalar logis. Namun, karena matematika adalah ilmu kuantitas, padahal ilmu-ilmu pengetahuan mencakup lebih dari kuantitas, perlu juga memperoleh kematangan masuk universitas lewat ilmu-ilmu yang lain. Yang paling menunjang dan memperluas perolehan lewat matematika adalah bahasa. Seseorang baru bisa bernalar dan bertutur secara dewasa, bila sudah menguasai ortografi, gramatika, dan sintaksis bahasanya sendiri.
Membaca ini semua, kita tidak heran mendengar seorang rektor universitas di Jerman berkata, “Setiap mahasiswa yang ingin studi kimia harus mempunyai nilai tinggi untuk matematika dan bahasa Jerman. Nilai baik untuk bahasa Latin dan bahasa Yunani diharapkan. Tidak begitu penting nilai-nilai fisika dan kimia”.
Seorang rektor lain mengatakan, “Kalau mau studi fisika, nilai untuk fisika dan kimia tidak penting, karena fisika dan kimia akan dipelajari di sini. Tetapi, nilai matematika dan bahasa Jerman harus tinggi, karena nilai-nilai itu menunjukkan apakah calon itu pandai atau tidak.”
Di Indonesia, cara kit menangani proses penerimaan mahasiswa sama sekali lain dan tidak memperhatikan aspek itu. Alasannya, karena unsur pokok pendidikan humaniora tidak ada dalam pendidikan kita. Karena itu, sistem Jerman lebih baik diterapkan di Indonesia.
Humaniora adalah gramatika, logika, dan retorika. Logika dan retorika tidak dapat berkembang, karena penguasaan gramatika bahasa Indonesia amat lemah. Mengapa? Sebab, mereka yang menulis, yang berbicara, yang berkhotbah, yang memberi kuliah, yang mengajar membuat kesalahan, yang oleh negara lain akan ditanggapi secara sinis dengan pertanyaan apakah orang itu sudah lulus SD atau belum. Reaksi ini juga timbul di Indonesia.
***
DARI tahun 1960 sampai tahun 1976, setiap hari Minggu saya ke desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, berkhotbah memakai bahasa Jawa. Ketika saya membuat kesalahan, saya tetap dipuji karena saya bukan orang Jawa. Tetapi, kalau seorang pastor Jawa membuat kesalahan yang sama, dia dikritik habis-habisan.
Seorang Jawa yang telah berpendidikan tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan itu. Dan, saya kira ini berlaku juga untuk semua suku bangsa. Namun, saat mengajar atau memberi kuliah atau menyusun skripsi untuk ujian sarjana, mereka memakai bahasa Indonesia secara salah, mereka dibiarkan. Karena, seperti bahasa Jawa bukan bahasa saya, demikian pula bahasa Indonesia bukan bahasa mereka!
Untuk kebanyakan orang Indonesia, bahasa Indonesia adalah de facto “a second language”, sementara bahasa ibu mereka sudah tidak dikuasai lagi. Ini berarti, bahasa Indonesia untuk calon intelektual kita bukan merupakan sarana humaniora. Bagaimana logika dan retorika bisa dikembangkan, kalau gramatika dari bahasa Indonesia tidak dikuasai secara mutlak?
Kesimpulan saya, pendidikan humaniora modern mungkin sekali di Indonesia, asal bahasa Indonesia sungguh-sungguh menjadi bahasa budaya. Bila bahasa Indonesia telah menjadi bahasa budaya, kita akan mampu juga menguasai bahasa asing. Mustahil mempelajari bahasa asing, bila di SD bahasa Indonesia tidak diajarkan secara optimal.
Jadi, syarat mutlak ialah tidak ada pengajaran bahasa Inggris di SD, karena mengganggu pengajaran bahasa Indonesia. Di Eropa dan Amerika, tidak ada satu negara pun yang mengajarkan bahasa asing di tingkat SD. Di kelas I SLTP sampai kelas III SMU, setiap minggu ada lima jam pelajaran bahasa Indonesia dan empat jam pelajaran bahasa asing; paling banyak dua bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan satu bahasa asing lain. Inilah syarat bagi kita orang yang berbudaya: menguasai dua bahasa asing.
Hanya ada satu kesulitan. Bila masing-masing bahasa asing mendapat dua jam pelajaran seminggu, mustahil dapat belajar sebuah bahasa. Karena itu, anjuran saya: hanya satu bahasa asing saja, yaitu bahasa Inggris. Dengan empat jam seminggu selama enam tahun, hasilnya akan cukup memuaskan.
J Drost SJ
Ahli pendidikan




Comments :